:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4740426/original/016844900_1707701886-fotor-ai-2024021282959.jpg)
Jakarta Dunia kripto dulunya dikenal sebagai gerakan akar rumput yang penuh semangat terbuka (open source). Saat pertama kali muncul, teknologi seperti Bitcoin dibuat agar siapa pun bisa melihat, memeriksa, dan bahkan ikut berkontribusi pada kode programnya.
Prinsip transparansi dan keterbukaan menjadi pondasi utama yang membuat orang bisa percaya pada sistem ini, karena semuanya bisa diperiksa sendiri.
Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi kripto, muncul juga tantangan dari sisi open source. Banyak proyek baru, seperti platform smart contract dan aplikasi keuangan terdesentralisasi (DeFi), yang kodenya disalin (disebut “fork”) oleh pihak lain untuk membuat produk serupa tapi hanya mengejar keuntungan, bukan idealisme awal.
Dikutip dari Cointelegraph.com, Jumat (2/5/2025), contohnya, muncul banyak versi tiruan dari Uniswap dan Ethereum yang lebih fokus pada kecepatan dan biaya murah, namun kurang memprioritaskan desentralisasi.
Karena itulah, beberapa tim pengembang mulai memilih jalur berbeda, yakni mereka menutup akses ke kode sumber mereka (closed source). Tujuannya adalah melindungi desain dan menghindari penyalahgunaan oleh peretas atau pesaing. Dengan membuat kode lebih sulit dianalisis, mereka berharap bisa mengurangi risiko diserang.
Tapi cara ini juga menuai kritik. Banyak yang menyebutnya “keamanan melalui kerahasiaan”, yaitu bukan karena sistemnya benar-benar aman, tapi hanya karena kelemahannya disembunyikan.
Pendekatan tertutup ini dianggap bertentangan dengan semangat awal dunia kripto, yang menjunjung tinggi keterbukaan, transparansi, dan kontrol dari komunitas, bukan dari segelintir orang saja. Apa yang dulu dimulai oleh para “cypherpunk” dan penggemar kebebasan digital, kini mulai berubah menjadi sistem yang justru mirip dengan institusi keuangan tradisional yang dulu ingin mereka lawan.
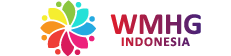
/2025/12/04/1281030887.jpg)
/2025/10/29/865650798.jpg)
/2025/12/08/659294977.jpg)
/2025/12/15/1325170386.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5027995/original/012021400_1732861121-fotor-ai-20241129131659.jpg)


/2022/04/01/764563844.jpg)
/2025/08/07/737618233.jpg)




:strip_icc()/kly-media-production/medias/4721215/original/050847100_1705711212-fotor-ai-2024012073921.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/1369941/original/055657900_1476098427-20161010-Harga-emas-stagnan-di-posisi-Rp-599-Jakarta-AY4.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/1369939/original/076856100_1476098426-20161010-Harga-emas-stagnan-di-posisi-Rp-599-Jakarta-AY2.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/2835792/original/038785100_1561357842-FOTO_0001.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5139939/original/076629500_1740130101-IMG-20250221-WA0002.jpg)
:strip_icc():watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,1180,20,0)/kly-media-production/medias/4898437/original/015266300_1721643866-965ec85f-ffdc-4ba4-83ff-1fa9c30e62eb.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5427523/original/002823900_1764393481-1000100028.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5498860/original/065344600_1770723530-WhatsApp_Image_2026-02-10_at_18.37.15__1_.jpeg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5497419/original/068689300_1770627953-Mensesneg_Prasetyo.jpg)