
wmhg.org – Di balik berita penyerangan rumah doa di Padang, Sumatera Barat (Sumbar), ada luka yang lebih dalam dari sekadar bangunan yang rusak dan korban fisik.
Insiden ini adalah cermin retak yang memantulkan wajah toleransi kita yang rapuh.
Jika kita tidak belajar, tragedi ini hanya akan menjadi angka dalam statistik kelam.
Berikut adalah empat pelajaran pahit yang harus menjadi bahan introspeksi dari peristiwa yang menjadi sorotan publik ini:
1. Miskomunikasi Adalah Eufemisme Berbahaya untuk Intoleransi
Menyebut kekerasan sebagai miskomunikasi adalah upaya menormalkan kebencian.
Ini meremehkan penderitaan korban dan melindungi pelaku dari label sesungguhnya: kaum intoleran.
Selama kita terus menggunakan kata ini, kita tidak akan pernah sampai ke akar masalah, yaitu ketidakmampuan sebagian kelompok untuk menerima keberadaan yang lain.
2. Anak-Anak Menjadi Korban Terakhir dari Kebencian
Saat orang dewasa berkonflik atas nama keyakinan, anak-anaklah yang menanggung akibat paling kejam. Mereka tidak tahu apa-apa tentang izin bangunan atau sengketa teologis.
Mereka hanya tahu rasa sakit dipukul kayu dan teror melihat orang-orang yang mereka percaya diserang. Tragedi Padang adalah pengingat paling brutal bahwa kebencian selalu memangsa kepolosan.
3. Diam Bukan Lagi Emas, Ia Adalah Persetujuan
Kasus seperti ini seringkali terjadi karena mayoritas yang baik memilih diam.
Mereka merasa tidak terlibat, padahal diamnya mereka adalah ruang hampa yang diisi oleh kaum minoritas yang bising dan beringas.
Pelajaran dari Padang adalah, tidak cukup hanya menjadi orang yang tidak intoleran. Kita harus menjadianti-intoleran—berani ber dan melawan saat melihat ketidakadilan terjadi di sekitar kita.
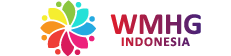
/2025/11/20/148874979.jpg)
/2021/11/18/1612827877.jpg)
/2023/07/27/1172885582.jpg)
/2022/03/08/639541023.jpg)



/2025/11/27/1262603760.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/3309036/original/007411800_1606469656-20201127-Upah-buruh-tani-naik-angga-1.jpg)

:strip_icc()/kly-media-production/medias/5203982/original/041738600_1745988471-30_april_2025-1.jpg)




:strip_icc()/kly-media-production/medias/3172732/original/048313800_1594117392-20200707-Harga-Emas-Pegadaian-Naik-Rp-4.000-7.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/2858898/original/006856400_1563614299-20190720-Gangguan-Bank-Mandiri-HERMAN-4.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/4826292/original/095830100_1715176226-fotor-ai-20240508204955.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/3172729/original/052282800_1594117386-20200707-Harga-Emas-Pegadaian-Naik-Rp-4.000-4.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5276247/original/033412300_1751948567-5.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/3490938/original/091266200_1624439228-20210623-Penjualan-Obat_-alkes_-dan-Vitamin-Meningkat-tallo-3.jpg)